
Opini oleh Andreas Ambesa
Pemuja.com – Bencana banjir bandang Sumatra sangat mengejutkan dunia. Selain korban jiwa yang lebih 1.000 orang, banjir ini bukan saja disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih menyakitkan: kerusakan alam, perusakan hutan secara masif, serta pengabaian pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Salah satu wilayah yang paling parah terdampak adalah Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah yang dulu dikenal sejuk, hijau, subur, dan menjadi tumpuan hidup bagi ribuan keluarga. Kini, daerah itu seakan berubah menjadi wilayah sunyi yang porak-poranda. Akses ke sana sangat sulit dijangkau, dan bantuan kemanusiaan terhambat oleh kondisi tanah yang terbelah, jalan yang hilang, dan desa yang terisolasi sepenuhnya.
Banjir itu datang bukan sebagai kejutan dari langit — melainkan sebagai buah dari pilihan manusia. Dari pembukaan hutan besar-besaran di kawasan hulu, dari lemahnya kontrol terhadap alih fungsi lahan, dari eksploitasi alam yang menutup mata terhadap risiko yang mengintai. Air bah membawa kayu-kayu berdiameter besar, seolah memperlihatkan bukti nyata bahwa hutan telah ditebang tanpa kendali.

Dalam hitungan menit, rumah hanyut, sawah hilang, dan harapan masa depan lenyap. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, harta, bahkan anggota keluarga. Tangis anak-anak, teriakan kesedihan, dan tatapan kosong orang dewasa yang kehilangan segalanya menciptakan suasana yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Tanah yang pernah hijau itu kini menjadi tempat air mata duka mengalir.
Namun ironinya selalu sama: kepedulian baru datang setelah bencana menelan semuanya. Setelah kerusakan terjadi, barulah rapat darurat digelar, barulah janji rehabilitasi dikumandangkan, barulah rencana konservasi dibahas kembali. Siklus ini terus berulang — alam rusak, bencana datang, manusia menyesal, lalu melupakan pelajarannya.
Aceh Tamiang mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar bukan hujan, bukan sungai, bukan banjir melainkan sikap manusia yang menganggap alam sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa akhir. Hutan seharusnya menjadi pelindung, bukan korban; sungai seharusnya menjadi sumber kehidupan, bukan saluran industri.
Pemulihan fisik penting, tetapi tidak cukup. Yang harus dipulihkan pertama-tama adalah cara berpikir kita tentang alam.
– Hutan bukan komoditas, melainkan penopang kehidupan.
– Lingkungan bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasinya.
– Pembangunan tanpa keberlanjutan bukanlah kemajuan — melainkan bencana yang menunggu giliran.
Hari ini Aceh Tamiang menanggung dukanya.
Tetapi duka ini bukan hanya milik mereka — ini adalah peringatan untuk semua.
Karena pada akhirnya, 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗸𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮 — 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗱𝗮𝗵𝘂𝗹𝘂 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗸𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗮𝗺.
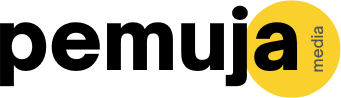













Leave a comment