Pemuja.com – Pergantian Menteri Keuangan Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Tak bisa dipungkiri, setiap perubahan di kursi strategis ini selalu memunculkan pro dan kontra di kalangan netizen.
Ragam opini publik pun bermunculan, termasuk dari Andreas Ambesa, seorang pengamat yang menilai langkah awal sang menteri baru patut dicermati.
Meski begitu, satu hal yang pasti, Purbaya Yudhi Sadewa tidak menunggu lama untuk menunjukkan gebrakan besar dalam upayanya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Bagaimana pandangan lengkapnya? Simak ulasan dalam Opini Cerdas Pedas berikut ini.

Janji Manis Pejabat Yang Gampang Memikat
Orang Indonesia cenderung cepat percaya pada 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 pejabat baru seperti Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu baru di era Prabowo) atau Jokowi dulu karena beberapa faktor budaya, sejarah, dan dinamika sosial-politik yang saling terkait.
Ini bukan fenomena unik, tapi cukup khas di Indonesia yang masih dipengaruhi warisan otoritarianisme dan harapan tinggi terhadap pemimpin “pembaru”. Ada beberapa catatan yang bisa dijelaskan secara bertahap berdasarkan pola yang sering muncul.
𝟭. 𝗖𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 “𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝘂” 𝗮𝘁𝗮𝘂 “𝗠𝗲𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁” 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗸 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻
Pejabat baru sering muncul dengan narasi sederhana, blak-blakan, atau janji pertumbuhan cepat, yang langsung menyentuh emosi rakyat yang lelah dengan status quo.
Jokowi dulu (sekitar 2012-2014) naik sebagai wali kota Solo dan gubernur Jakarta yang “dekat rakyat”: gaya blusukan, bicara pelan tapi meyakinkan, dan janji infrastruktur yang terasa nyata. Ini membuatnya terlihat autentik, bukan elite jauh.

Hasilnya, survei approval rate-nya tinggi karena rakyat melihatnya sebagai anti-korupsi dan pro-rakyat, meski kemudian banyak janji yang dianggap ingkar (seperti soal dinasti politik anaknya).
Begitu juga Purbaya, yang baru dilantik September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia langsung sesumbar soal ekonomi tumbuh 6-7% dalam beberapa tahun ke depan, bicara ceplas-ceplos seperti “jurunya mabuk” atau motivator pasar.
Meski dikritik sombong dan kurang empati (misalnya meremehkan demo 17+8 sebagai “suara minoritas”), banyak yang percaya karena dia terlihat berani dan 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵, kontras dengan gaya teknokrat Sri Mulyani yang lebih hati-hati.
Ini menciptakan 𝘦𝘶𝘧𝘰𝘳𝘪𝘢 sementara, apalagi di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi dan 𝘳𝘦𝘴𝘩𝘶𝘧𝘧𝘭𝘦 kabinet.
𝟮. 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮 𝗛𝗶𝗲𝗿𝗮𝗿𝗸𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 (𝗙𝗲𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗥𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻)
Secara budaya, Indonesia punya sisa-sisa sikap feodal di mana pejabat dianggap “punya wewenang Ilahi” atau setidaknya lebih tahu.
Mochtar Lubis dalam pidatonya tahun 1970-an menyebut orang Indonesia cenderung “bersikap feodal” dan “percaya takhayul”, termasuk mudah percaya pada figur berkuasa tanpa verifikasi mendalam.
Jokowi sendiri pernah bilang dia “agak percaya” poin itu, karena banyak pejabat yang suka takhayul—tapi ini juga berlaku pada rakyat yang melihat pejabat sebagai “pemimpin alami”.
Ini diperkuat sejarah Orde Baru (era Soeharto) di mana media dikontrol, kritik dibungkam, dan rakyat dibiasakan patuh. Hasilnya, sekarang meski ada kebebasan berpendapat, banyak yang masih refleks percaya 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 resmi dulu, baru nanti kritis kalau terbukti salah.
Contoh: Jokowi awalnya dipuji sebagai “presiden dari akar rumput”, tapi kemudian dituduh bangun dinasti via putranya Gibran Rakabuming Raka—tapi awalnya, harapan itu bikin orang cepat yakin.
𝟯. 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹, 𝗕𝘂𝘇𝘇𝗲𝗿, 𝗱𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗲𝗯𝗮𝗿
Di era digital, 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 pejabat baru langsung viral via X (Twitter), TikTok, atau berita online, sering diframing positif oleh 𝘣𝘶𝘻𝘻𝘦𝘳 atau pendukung.
Jokowi dulu dibantu narasi “Jokowi hebat” yang dibangun lewat survei dan media, membuat kebohongan kecil (seperti janji tak cawe-cawe pilpres 2024) terlihat minor.
Purbaya juga: meski blunder soal demo, ada opini yang bilang “lebih baik sesumbar daripada diam seperti menteri lain”, karena bikin gampang ditagih hasilnya.

Rakyat cenderung percaya berita baik dulu (seperti janji pertumbuhan), tapi cepat kecewa kalau buruk—tapi fase “percaya cepat” itu dimanfaatkan untuk legitimasi awal.
Sejarah korupsi pejabat lama bikin orang haus figur baru, tapi ini juga bikin rentan 𝘧𝘳𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨: “Ini yang kita butuh, yang lama gagal.”
𝟰. 𝗞𝗼𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹-𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶: 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻
Indonesia punya populasi muda yang ingin perubahan cepat, tapi ekonomi sering lesu (inflasi, pengangguran). Pejabat baru seperti Jokowi (fokus infrastruktur) atau Purbaya (janji likuiditas Rp200T ke pasar) terlihat sebagai “penyelamat”.
Rakyat bawah, yang mayoritas, lebih percaya janji “kerja dan makan enak” daripada analisis rumit. Ini mirip populisme: Jokowi menang 2014 karena harapan, bukan rekam jejak panjang.
Tapi ada sisi negatif: cepat percaya bikin lambat kritis. Seperti Basuki Tjahaja Purnama dulu (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017), yang arogan tapi diberi kesempatan karena “𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘴 𝘭𝘰𝘶𝘥𝘦𝘳”—mirip Purbaya sekarang. Kalau kebijakan gagal, baru ramai kritik, tapi awalnya sudah terlanjur dukung.
Intinya, ini campuran antara budaya patuh, harapan emosional, dan strategi politik yang pintar. Bukan berarti semua orang begitu—ada juga yang skeptis dari awal—tapi mayoritas terpengaruh karena butuh “cerita sukses” di tengah masalah nyata.
Kalau mau hindari, biasakan verifikasi fakta dan lihat track record, bukan cuma kata-kata manis. Semoga Purbaya atau siapa pun bisa buktiin janjinya, biar kepercayaan itu nggak sia-sia.
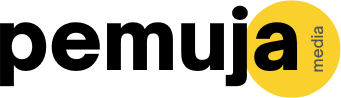













Leave a comment